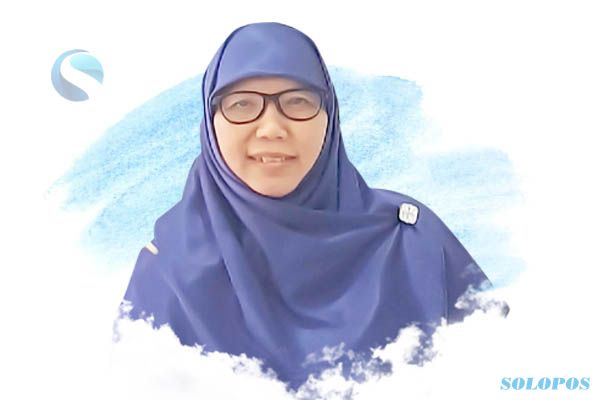Solopos.com, SOLO – Dunia media sosial menyajikan banyak ruang kebebasan. Terbuka menampung pikiran dan pilihan sikap yang terkadang keblabasan. Kasus-kasus populer yang terus bergulir menyajikan beragam cerita.
Jangan pernah main-main dengan warganet kalau tidak mau diserbu hujatan dan makian ketika berbeda dengan kebanyakan pendapat mereka. Saat yang kita sebut empati pada figur atau kelompok tertentu berbenturan dengan pilihan orang lain, bersiaplah dengan perang opini. Terkadang lebih mendekat pada fitnah dan pembunuhan karakter.
Promosi Tragedi Simon dan Asa Shin Tae-yong di Piala Asia 2023
Bermain di media sosial dengan seluruh konsekuensi logisnya mengharuskan kita pandai-pandai memilih dan memilah apa yang layak masuk dalam rekaman kognitif kita. Kita harus peka dengan suasana batin kita sendiri ketika hendak menangkap peristiwa.
Empati berasal dari bahasa Yunani empatheia yang bermakna ketertarikan fisik. Seorang psikolog pendiri aliran psikologi individual, Alfred Adler, menyatakan empati adalah suatu penerimaan seseorang terhadap perasaan orang lain dan berusaha menempatkan diri pada posisi orang lain itu.
Tokoh psikoanalisis Sigmund Freud menyebut sebagai memahami tetapi tidak mempunyai arti emosional bagi kita. Sejarah empati selama ini lebih dikenal bersumber dari filsafat estetika.
Kata einfuhlung yang diterjemahkan sebagai empati oleh Edward Bradford Titchener, murid Willhelm Wundt (Bapak Psikologi Modern) pada abad ke-19, menjadi tonggak awal pemahaman tentang empati.
Robert Vischer pada 1846, ketika membahas mengenai karya seni, memaknai empati dengan masuk ke dalam untuk memproyeksikan perasaan kita dalam karya tersebut.
Empati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi diri dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.
Dalam proses tersebut sering kali justru yang dominan kemudian adalah perasaan kita sendiri. Kita terkadang menggunakan kata empati untuk menutupi niat terselubung, betapa kita ingin terakui sebagai pihak yang paling depan membela.
Kita sepertinya memang terbiasa terbagi dalam dua kubu yang saling bertikai. Rasa empati pada kondisi salah satu pihak menjadikan mereka menabukan melihat rasa di pihak lainnya. Empati diklaim secara mutlak sebagai milik mereka dengan cara-cara subjektif yang diyakini.
Pada tahun politik seperti sekarang ini gegap gempita pembelaan pada salah satu calon pemimpin menjadi sajian dan tontonan yang kerap kali bukanlah tuntunan. Ketika merasa jagoannya adalah yang paling terzalimi, narasi-narasi monoton penuh kebencian yang terkadang tidak dipahami maknanya menjadi mudah terucapkan.
Mengapa warganet bisa militan berempati tanpa peduli lagi adab kepatutan lainnya? Niat awal memang menempatkan rasa pada posisi keprihatinan atas apa yang terjadi pada seseorang. Selanjutnya pembelaannya menjadi tanpa nalar lagi. Kata-kata kotor, fitnah, rumor, dan makian saling berebut mencari panggung terbaik di media sosial.
Mereka membenci makian tetapi menduplikasinya. Mereka tidak suka seseorang menyakiti, tetapi justru dirinya sendiri berpotensi menyakiti hati orang lain. Atas nama empati apakah adab kesopanan diabaikan? Demi niat membela lalu tatanan norma kepatutan ditinggalkan.
Tak henti-hentinya kita disuguhi berita dan konten saling menjatuhkan sesama anak bangsa hanya karena beda pilihan. Tidak ditemukan lagi kesejukan berteman meski harus berbeda pilihan. Semuanya terbelah dan harus berada di sisi yang berbeda untuk siap menerkam satu dengan lainnya.
Empati kepada satu figur tokoh menjadi paradoks kemanusiaan yang menahun. Kalau Anda belum bosan dengan drama perdebatan antara dua kubu mari kita bicara empati sesuai dengan makna aslinya. Empati dalam budaya Jawa disebut dengan tepa slira.
Penelitian Depow, Francis, dan Inzlicht (2021) menunjukkan pengalaman empati ini berhubungan positif dengan perilaku prososial, suatu hubungan yang tidak ditemukan dalam ukuran sifat. Seperti kata psikolog Alfred Adler, empati adalah kita melihat dengan mata orang lain, mendengarkan dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan hati orang lain.
Nilai Kemanusiaan
Plato mengatakan bentuk tertinggi dari pengetahuan adalah empati karena empati membutuhkan tujuan mendalam yang lebih besar daripada memahami diri sendiri. Banyak orang mudah peduli pada seseorang yang diduga teraniaya oleh suaminya tetapi kenapa bisa sangat cuek dengan puluhan orang yang dipenjara atau terambil nyawanya karena perbedaan politik.
Jawabannya harus kembali pada konsep empati dalam pikiran masing-masing orang. Ada kepentingan-kepentingan yang menyertai rasa empati itu. Ada alasan kedekatan emosional, ada kesungkanan perasaan, atau ada keterpaksaan kondisi yang menjadikan mereka beramai-ramai berempati.
Dorongan untuk berempati dimungkinkan ketika korban nyata dan dekat dengan kepentingan pribadinya. Memang tidak ada yang salah dengan alasan pribadi di balik sikap empati. Ketika empati menjadi dalil pembenaran seseorang untuk menyingkirkan orang lain dengan cara-cara yang diperhalus meski menyakiti maka bisa jadi sasaran empati tidaklah tepat.
Beberapa orang sulit berempati pada kecelakaan pesawat karena tidak ada satu pun korban yang dikenal. Hati menjadi lebih mudah tersentuh ketika ada bagian dari hidup kita berada di pesawat tersebut. Berempati pada hal yang abstrak memang sulit meski wujud kejadiannya sebenarnya nyata terpampang jelas di depan mata.
Pada beberapa kasus, rasa empati seseorang dimanipulasi untuk bertindak di luar nalar agar terkesan benar. Ternyata konsep empati berlaku secara tidak pasti dan cenderung subjektif. Psikolog dari Universitas Yale, Paul Bloom, menganggap rasa empati ini bisa berpotensi bermasalah.
Kisah seorang gadis yang didahulukan untuk diperiksa oleh seorang dokter karena mendapatkan simpati dari banyak orang tanpa sadar justru berpeluang mengambil hak perawatan pasien lain yang sudah lebih dahulu masuk dalam daftar antrean.
Banyak kasus viral yang mendapat empati dari warganet lebih mudah menemukan jalan pintas untuk diperhatikan daripada kasus yang masih tenggelam di ruang sunyi penderitaan. Bisa jadi kasus-kasus yang tersembunyi itu jauh lebih memerlukan kecepatan tindakan.
Orang lebih peka terhadap yang secara terus-menerus terberitakan daripada kasus yang hanya sekilas saja melintas. Kepedulian berjemaah serentak muncul bukan karena spontan berempati, tetapi karena kehebohan rasa peduli masyarakat yang membuat tidak mau tertinggal.
Mari kembali menempatkan empati sesuai dengan makna aslinya. Jangan lagi mengumbar kalimat toxic atas nama empati. Hentikan beradu asumsi atas kata empati yang tak sesuai dengan kaidah asal bahasanya.
Sudahi bertengkar memerkarakan pilihan rasa empati yang malah berujung pada permusuhan pribadi atau kelompok. Kalimat manis dari penulis lagu Morgan Harper Nichols ini mungkin bisa mewakili apa itu yang disebut dengan empati.
This is empathy: Let me hold the door for you. I may have never walked a mile in your shoes, but I can see that your soles are worn and your strength is torn under the weight of a story I have never lived before. So let me hold the door for you. After all you’ve walkel throught, it’s the least I can do.
Kita mungkin tak pernah melangkah bersama dan berada dalam sisi ruang yang sama, tetapi nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk berpikir, berbicara, merasakan, dan bertindak dengan nalar sehat bahwa manusia harus saling menyayangi, menghormati, dan mengerti untuk tidak menyakiti. Mari berempati atau kita akan mati tanpa pernah dikenali.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 3 Juli 2023. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Doktoral Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta)