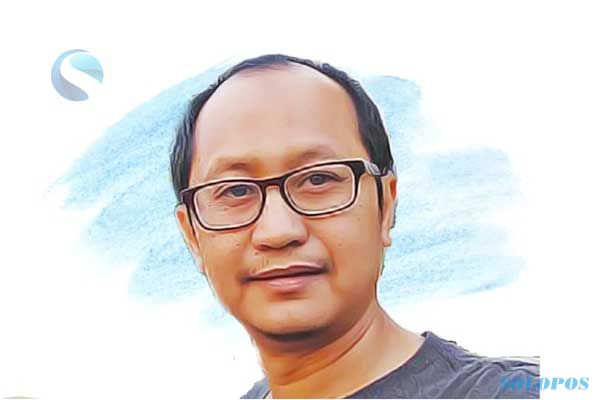Berkali-kali ibu saya yang umurnya 77 tahun mendapatkan konten hoaks di Whatsapp group (WAG) keluarga. Ada hoaks kesehatan, bencana, hingga politik. Saat Pemilu 2019 dan 2024, hoaks politik mendominasi isi WAG keluarga. Namun, berkali-kali juga saya harus menjelaskan konten itu tidak benar. Walaupun sebagian adalah fakta, dominan hoaksnya. Terakhir, saya harus menjelaskan kepada ibu bahwa tidak semua yang diterima di WAG, Youtube, maupun platform media sosial lainnya sebagai sebuah kebenaran. Walau ada foto atau video yang terkesan menguatkan hoaks itu, saya bilang mudah sekali orang merekayasanya. Bahkan sekarang ada artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang dipakai untuk mengelabuhi orang.
Di dunia media massa juga demikian. Walaupun berita adalah fakta, saya perlu menyampaikan bahwa apa yang disajikan media massa tidak identik dengan fakta. Peristiwa yang benar-benar terjadi adalah realitas objektif. Misalnya kecelakaan lalu lintas adalah realitas objektif. Benar-benar terjadi. Lalu wartawan datang ke lokasi kecelakaan, mengumpulkan bahan dengan observasi, wawancara, hingga riset mengenai kecelakaan itu. Hasilnya adalah sebuah produk jurnalistik yang dimuat di koran, media online, televisi, maupun radio.
Promosi Gonta Ganti Pelatih Timnas Bukan Solusi, PSSI!
Apakah berita di berbagai media tentang kecelakaan itu adalah fakta atau realitas? Ya pasti dong. Ada peristiwanya. Realitas itu disusun oleh wartawan berdasarkan apa yang dia lihat atau mengacu data yang didapatkannya. Namun, realias objektif atau peristiwa itu levelnya berbeda dengan realitas yang ada di media, yaitu berita. Dosen saya di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Mursito B.M. menyebut realitas media untuk menggambarkan berita. Ada perbedaan antara realitas media dan realitas empirik. Menurut Mursito, berita adalah hasil konstruksi atas peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri. Wartawan mengubah realitas empirik (peristiwa) itu menjadi realitas simbolik (berita). Karena itu, pembaca atau pemirsa kadang mendapati wartawan dari berbagai media membuat berita dengan angle berbeda, padahal sumbernya dari peristiwa sama. Liputannya pun berbarengan.
Walaupun realitas media itu tergantung pada konstruksi wartawan, tetapi masih dibatasi oleh aturan. Ada prinsip dan kode etik jurnalistik yang wajib diikuti oleh wartawan ketika menyusun berita. Namun, tetap kita menyebut berita adalah fakta yang dikonstruksi oleh wartawan atau media.
Hal ini berbeda dengan hoaks atau misinformasi/disinformasi yang sering diterima oleh ibu saya atau Anda. Saya yakin Anda sering menerima konten hoaks di media perpesanan maupun media sosial. Hoaks atau sering disebut juga misinformasi dan disinformasi ini memang merebak belakangan ini, apalagi pada tahun politik. Pendukung calon presiden saling menyerang untuk menjatuhkan lawan dengan membuat hoaks. Fitnah dan kebohongan jadi strategi menyerang lawan.
Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, hal ini terjadi secara massif. Lalu bagaimana dengan Pemilu 2024?
Dalam Indonesia Fact-Checking Summit 2024 yang diadakan sebelum Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Palembang, Kamis (2/5/2024), Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyebut pada 2019, pihaknya mendapati 997 hoaks, yang berkaitan dengan politik 488 konten. Pada 2023 atau menjelang Pemilu 2024, terdapat 2.330 hoaks, yang terkait politik (pemilu) mencapai 1.292. Jadi ada peningkatan. Pada Januari-Februari 2024, ditemui 696 hoaks dan yang terkait pemilu mencapai 440. Jadi, hoaks tetap banyak.
Dalam acara itu, Ross Tapsell dari Australian National University (ANU) menyinggung soal misinformasi/disinformasi pada pemilu di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Pada Pemilu 2024 juga terjadi disinformasi. Yang menarik, Ross Tapsell menyebut terjadi toxic positivity. Dalam dunia psikologi, istilah itu berarti berpikir positif yang kebablasan sehingga menjadi racun. Akan tetapi, dalam konteks politik, konteksnya berbeda. Nicole Curato (2022) dari Universitas Canberra melihat Pemilu 2022 di Filipina yang dimenangi oleh Ferdinand Marcos Junior (Jr) berlangsung kampanye getaran baik (good vibes) dan positif yang beracun (toxic positivity). Dalam kampanye, Marcos Jr. lebih banyak menyerukan persatuan dan damai. Dia menampilkan diri sebagai tokoh yang tak ingin konflik, menghindari membicarakan masa lalu yang kelam, hingga tak mau debat yang memecah belah. Padahal orang tahu dia adakah anak diktator Marcos Sr.
Di Indonesia, Ross Tapsell menyebut misinformasi/disinformasi tetap ada dalam pemilu. Akan tetapi, terjadi perubahan. Dalam analisisnya di www.cigionline.org, Ross Tapsell menyebut misinformasi/disinformasinya tak sama dengan yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019. Pada 2024, tak banyak fitnah dan kebohongan. Tudingan komunis hingga tak islami juga sudah berkurang.
Pemenang dalam Pemilu Presiden 2024 Prabowo Subianto mengubah diri menjadi sosok yang berbeda. Dulu, Prabowo lekat dengan sosok tegas, bahkan cenderung emosional. Ternyata, dengan karakter seperti itu, dia malah kalah dua kali.
Dia berubah 180 derajat. Menurut Ross Tapsell, sosok Prabowo di hadapan publik berubah dari seorang pria berusia 72 tahun yang dua kali kalah, yang terkadang tampak lelah dan tidak sehat serta tertinggal dalam jajak pendapat, menjadi seorang kakek yang ramah dan gemoy dengan tarian unik, tidak pernah tampak seperti pernah kalah.
Dia menghindari taktik kampanye negatif, malah membangkitkan energi positif. Dalam debat, Prabowo sering kali setuju dan mengucapkan terima kasih kepada lawan-lawannya.
Pertanyaan dari Ross Tapsell adalah apakah ini disinformasi? Bisa jadi ada yang setuju, ada pula yang tidak. Ada pula yang menganalisis bahwa ini merupakan strategi pencitraan yang berperan mengerek dukungan. Dalam komunikasi politik ada yang namanya propaganda untuk mendapatkan dukungan. Dalam dunia bisnis, ada komunikasi pemasaran dan periklanan. Semuanya untuk membentuk citra publik yang akan berdampak positif. Akan tetapi, publik harus ingat citra ada yang sesuai dengan fakta, ada pula yang tidak. Bisa jadi, citra yang dilihat publik adalah realitas buatan atau artifisial. Karena sekarang zamannya media sosial, saya menyebutnya realitas di dunia maya alias digital. Apakah citra itu akan bertahan atau luntur, biarlah waktu yang akan menjawabnya.
Artikel ini telah dimuat di Harian Umum Solopos, Jumat, 3 Mei 2024. Penulis adalah Wartawan Solopos.