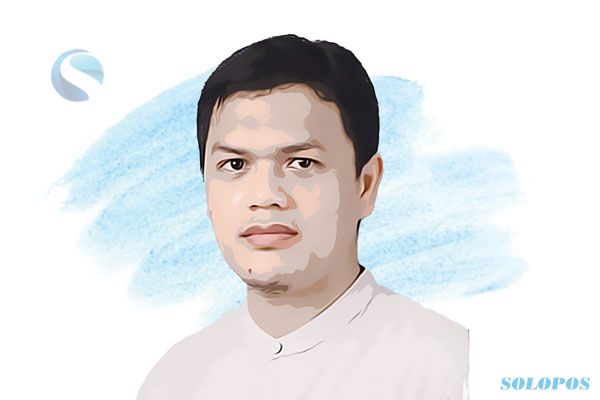Solopos.com, SOLO – Sektor agraria adalah sektor penting bagi sebuah negara dengan sumber daya tanah yang luas dan subur seperti Indonesia. Dalam perspektif geologis dan sosiologis, tanah adalah sumber penghidupan, tempat bercocok tanam, identitas suatu individu dan kelompok, serta bagian dari sumber kekuasaan.
Secara historis, di Indonesia sebagai negara agraris juga sangat peduli terhadap persoalan pertanian dan tanah. Ini sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat
UUPA tonggak pembaruan agraria yang memuat transformasi hukum agraria masa kolonial menuju hukum nasional. Dasar normatif ini sebagai tanda untuk mengakhiri feodalisme dengan membatasi penguasaan lahan, distribusi kepemilikan bagi petani, dan merupakan wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tentang pemerataan ekonomi.
Merujuk norma dasar ini menjadi bentuk perhatian serius untuk menjaga tanah kita agar tetap produktif dan lestari agar dapat diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Muhammad Azhar berpendapat berangkat dari pembacaan atas realitas dan fenomena yang terjadi di masyarakat maka perlu ada tata kelola agraria yang baik.
Ia menyebut di antara beberapa fenomena tersebut adalah masalah swasembada pangan yang terkesan lambat, rusaknya ekosistem yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan atau konversi lahan (deforestasi), adanya konflik agraria yang semakin hari kian meningkat, dan semakin terpinggirkannya nilai-nilai dan/atau komunitas adat atas tanah mereka.
Sektor pertanian mengalami masalah dilematis. Pada musim kemarau dan tidak ada air, tanah tidak bisa ditanami. Imbasnya petani mengalami kesulitan ekonomi, tapi pada musim hujan petani masih banyak yang mengalami gagal panen.
Pertumbuhan padi tidak maksimal disebabkan banyak gulma dan banyak tanaman padi yang rusak karena terjadi hujan lebat atau terkena banjir. Ditambah kebijakan pemerintah tentang pupuk semakin mempersulit sektor pertanian.
Beragam fakta ini mudah kita jumpai di depan mata. Beragam fakta ini juga yang melatarbelakangi perlunya pengelolaan lahan pertanian yang lebih arif dan berorientasi pada nilai spiritualitas. Terutama nilai-nilai spiritualitas yang dijiwai nilai agama dan tradisi.
Sebenarnya ada ikhtiar untuk masalah ini. Nilai spiritualitas itu diterjemahkan dalam bentuk fikih agraria. Muhammad Soehada menjelaskan ada enam nilai dasar dalam fiqih agraria yang (salah satunya) dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Keenam nilai itu adalah nilai tauhid, moralitas, kemaslahatan, keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Soehada menerangkan bahwa keenam nilai dasar itu harus tercermin terutama dalam proses pembuatan hukum, penegakan hukum, jaminan proses pemerataan kesejahteraan rakyat, dan solidaritas umat dan bangsa.
Pemantapan Solusi
Meskipun secara regulasi dan kebijakan sudah dibuat dengan sedemikian rupa, implementasi terkadang masih terkesan belum maksimal. Jauh panggang dari api. Dari waktu ke waktu sawah menyempit, tergantikan perumahan dan kawasan industri.
Imbasnya beragam masalah sosial dan ekologis terjadi. Seperti masalah swasembada pangan yang terkesan lambat karena produksi menurun, rusaknya ekosistem yang ditimbulkan oleh alih fungsi atau konversi lahan, dan adanya konflik agraria yang semakin hari kian meningkat terutama terkait dengan ketahanan pangan.
Lebih parah lagi semakin terpinggirkannya nilai dan/atau komunitas adat sehingga mengakibatkan terjadinya krisis karakter yang semakin agresif. Lahan yang tersisa dijadikan sebagai sarana untuk dipersaingkan atau perebutan hak atas tanah.
Melihat gejala atau fenomena ekologis dan sosiologis yang demikian, tampaknya perlu penguatan-penguatan dari sisi kemanusiaan untuk kembali menumbuhkan sikap peduli terhadap alam dan sikap arif dalam menciptakan ekosistem dan ekososial yang seimbang. Baik itu ekosistem alam maupun ekosistem kemanusiaan.
Bagi masyarakat Jawa, tanah, alam, dan pertanian seperti menjadi satu tubuh yang saling melengkapi hingga menjadi sebuah struktur budaya atau tradisi yang mengakar kuat. Penguatan ini dapat dilakukan dengan intensifikasi atau pendampingan terprogram terkait nilai-nilai spiritualitas tentang etos kerja dan produktivitas bagi masyarakat petani.
Aktivitas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan dan ketidakseimbangan alam yang semakin parah. Terjadinya pencemaran lingkungan, iklim tidak menentu, dan suhu udara sangat ekstrem adalah di antara indikasinya.
Salah satu motivasi adalah belajar kembali dari falsafah hidup masyarakat Jawa yang memiliki pemikiran menarik seputar pertanian dan kosmologi. Menurut Branders (1889), masyarakat Jawa telah memiliki sepuluh dasar nilai kehidupan asli (orisinal) yang telah ada sebelum masuknya agama-agama.
Sepuluh nilai tersebut yaitu pertanian, sawah, irigasi, pelayaran, perbintangan, wayang, gamelan, batik, metrum (pola dalam tembang macapat), cor logam, mata uang, dan sistem pemerintahan. Dasar kebudayaan tersebut ada sejak zaman Jawa kuno dan merupakan kedaulatan spiritual khas bagi masyarakat Jawa.
Falsafah Jawa ini digunakan oleh masyarakat untuk hidup memakmurkan Tanah Jawa. Falsafah hidup ini juga sebagai simbol lengkap hukum-hukum untuk kemakmuran di Tanah Jawa. Salah satu bagian penting yang disebutkan dengan jelas atau eksplisit dalam falsafah Jawa di atas adalah tentang pentingnya pertanian, sawah, dan irigasi.
Hal lain yang menarik dari falsafah hidup masyarakat Jawa adalah falsafah kesadaran kosmis yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam semesta beserta isinya. Kesadaran kosmis ini terkadang diceritakan oleh masyarakat Jawa dengan berbagai ritual sesaji dengan falsafah sakabehing kang ana manunggal kang kapurba lan kawasesa dening Kang Murbeng Dumadi.
Artinya semua yang ada di semesta adalah satu, yang ada berasal dari Sang Pencipta (manunggal). Alam kecil (mikrokosmos) dengan alam besar (makrokosmos) adalah menyatu. Alam dan seisinya termasuk manusia adalah satu kesatuan.
Angkasa (langit) adalah bapak dan Bumi (tanah) adalah ibu. Manusia dibangun dari unsur cahaya (cahya lan teja) dan unsur bumi (tanah, banyu, geni, lan angin, utawa hawa). Jika alam ini sakit atau rusak maka manusialah yang merasakan pedihnya.
Manusia yang menderita ketika alam ini rusak. Manusia juga yang akan merasakan akibatnya jika alam ini tidak seimbang. Di luar unsur magis dan mitologi masyarakat Jawa, betapa manusia seharusnya memiliki perasaan yang dapat menyatu dengan alam, sehingga menghadirkan sikap dan perilaku untuk perduli dengan alam.
Manusia memiliki kesadaran lingkungan untuk tidak merusak. Manusia memiliki kesadaran spiritual sebagai fondasi mengelola alam dan pertanian dengan sebaik-baiknya.
Alam dapat dimanfaatkan, tapi tidak untuk dieksploitasi hingga merusak. Alam menyediakan beragam kebutuhan kita, maka tugas kita adalah menjaga dan melestarikan alam.
(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 8 Maret 2024. Penulis adalah dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta)